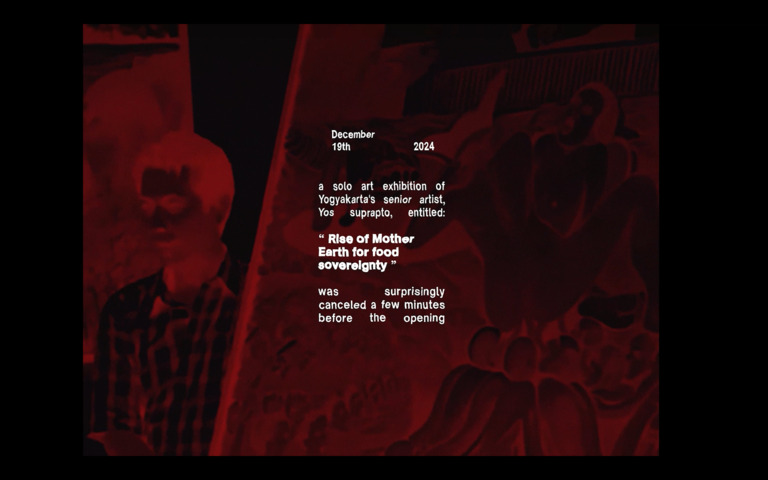The camera that lacks respect for human beings distorts the truth. If these principles are respected, there is no objection to the meticulous reconstitution or staging of scenes. –– Henry Storck
Kehadiran kamera selalu berkelindan dengan kuasa, gagasan, dan pilihan atas apa yang ada di depannya. Melalui agensinya, pembuat film membingkai, menyunting, dan menginterpretasi apa yang direkam dan akhirnya terekam. Cermin polos realitas bukanlah semata yang nampak di layar, ia adalah pantulan yang diarahkan oleh sang pembuat. Namun, kamera juga dapat menjebak kita untuk berhenti pada siapa yang dihadirkan, alih-alih bertanya tentang apa yang sedang dipersoalkan.
Dalam ekosistem produksi film dokumenter secara global, pendanaan dan festival memiliki kecenderungan untuk mendukung narasi yang bertumpu pada ketokohan. Ketokohan dianggap sebagai jalan tercepat untuk menarik perhatian, terutama ketika hendak membicarakan narasi besar. Tokoh yang kuat seolah menjadi tumpuan yang paralel dengan kuatnya cerita. Kecenderungan ini kemudian menjadi bagian dari praktik produksi dokumenter di Indonesia hingga hari ini. Konsekuensinya, film kerap berjalan di garis tipis antara profil yang merayakan capaian tokoh dengan narasi yang memberi ruang untuk menginterogasi hal-hal di sekitarnya. Siapa sering kali mengalahkan apa. Penonton meninggalkan ruang putar dengan rasa kagum, tetapi tidak selalu dengan pemahaman atas kondisi, struktur, atau sistem yang membentuk sang tokoh. Dalam situasi ini, mungkin saja kita perlu mempertanyakan posisi kita sebagai pembuat dan penonton: apa yang hilang ketika sorotan berhenti pada penokohan?
Kuasa pembuat film dalam menempatkan kamera berperan menyusun arah narasi. Setiap bingkai dan potongan adalah keputusan untuk menegaskan cara pandang yang tak terbatas pada pilihan estetika dan teknis saja. Melalui pilihan inilah, ruang interpretasi bagi penonton terbuka. Film tak hanya berhenti pada siapa yang ditonton, tetapi mengajak kita untuk membaca, mengalami, bahkan mempertanyakan narasi yang dihadirkan. Apakah kita hanya melihat sekumpulan ibu-ibu tekun yang lihai menenun di See a Mother, a Wife, and a Weaver (Suharditia Trisna Anugerah, 2025)? Atau, dapatkah kita melihat NH Dini tak hanya dari sorot kagum orang-orang yang menyayanginya di NH Dini (Ardian Parasto, 2024)? Mungkin pula, kita perlu menyelam lebih dalam atas momen-momen yang dihadirkan dalam The Silenced Soil (Dara Asia, 2025) dan The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace (Arfan Sabran, 2025).
Film-film dengan kecenderungan ketokohan ini tak melulu menjebak kita pada glorifikasi. Sebaliknya, mereka dapat menjadi tantangan untuk melihat melampaui yang diperlihatkan. Jika kamera yang menghormati subjeknya dapat menghadirkan realitas, maka mungkin tanggung jawab kita sebagai penonton adalah mempertanyakan ketika ia justru menempatkan subjek sebagai sebuah monumen.